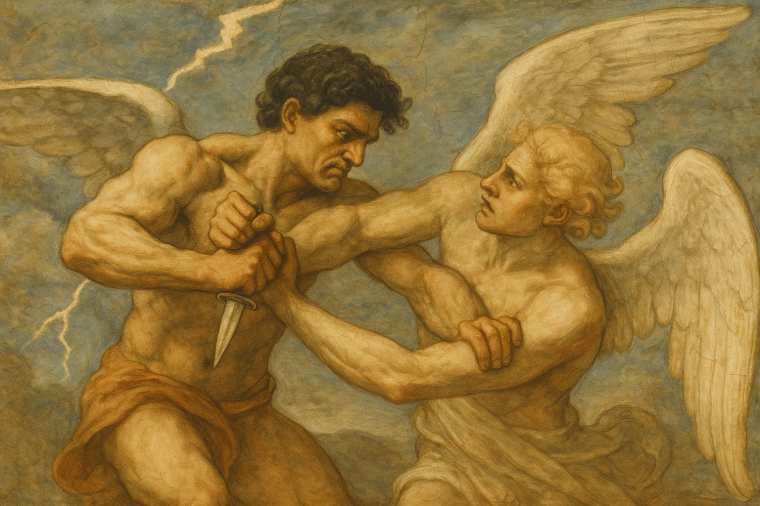Ringkasan
- Generasi pertama membangun; generasi kedua sering hanya menikmati. Itu pola antropologis universal, bukan sekadar psikologis.
- Solidaritas komunitas yang dulu membebaskan berubah menjadi zona nyaman yang menumpulkan etika kerja.
- Nilai “kita bekerja bersama” merosot menjadi “orang lain akan mengerjakan ini.”
- Ketergantungan yang dilembutkan oleh bahasa idealisme membuat komunitas tampak hidup, tetapi secara moral mati.
- Tanda stagnasi paling jelas: kerja menjadi simbolik, bukan kontribusi nyata.
Setiap komunitas lahir dari kebutuhan — dan kebutuhan adalah bentuk paling murni dari kecerdikan manusia.
Ketika sumber daya langka, manusia menemukan cara untuk berbagi. Ia menciptakan sistem barter, ritus gotong-royong, atau lembaga patronase untuk bertahan hidup bersama. Solidaritas adalah inovasi paling awal manusia. Namun sejarah menunjukkan bahwa begitu kebutuhan itu terpenuhi, solidaritas perlahan berubah bentuk. Ia kehilangan daya dorongnya dan menjadi kebiasaan, bahkan candu.
Fenomena ini berulang dalam hampir setiap fase peradaban manusia. Setelah Revolusi Neolitik, manusia tidak lagi bergantung pada perburuan, melainkan pada hasil pertanian yang stabil. Surplus pangan memungkinkan terbentuknya struktur sosial baru — pemimpin, imam, pengrajin, dan birokrat. Tapi seiring meningkatnya keamanan, lahirlah generasi yang tak lagi memahami penderitaan pendahulunya. Mereka lahir dalam kenyamanan yang dibangun oleh orang lain, lalu menganggap sistem itu akan menopang mereka selamanya. Seperti anak bangsawan yang tumbuh di istana, mereka menikmati buah kerja keras masa lalu tanpa merasa perlu menanam lagi.
Dalam bahasa antropologi, kita menyebut ini sebagai kemerosotan fungsional dalam sistem sosial stabil. Jared Diamond menulis dalam Collapse bahwa peradaban yang paling berisiko bukanlah yang miskin sumber daya, tetapi yang sukses — karena kemakmuran menciptakan ilusi keberlanjutan.
Bangsa Maya, misalnya, mengembangkan sistem irigasi dan arsitektur yang luar biasa, tapi gagal menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan tekanan populasi. Mereka menganggap sistem lama yang telah menyelamatkan nenek moyang mereka akan selalu cukup. Dalam setiap lapisan sejarah, pola ini sama: manusia menjadi korban dari stabilitas yang mereka ciptakan sendiri.

Kita bisa melihat pola serupa dalam bentuk yang lebih kecil — komunitas modern yang lahir dari idealisme. Banyak organisasi nirlaba, lembaga budaya, atau kolektif seni dimulai dari solidaritas sejati: beberapa orang berkumpul karena frustrasi terhadap sistem industri yang tertutup. Mereka menciptakan ruang alternatif di mana nilai kemanusiaan, kolaborasi, dan pendidikan menjadi inti. Namun setelah beberapa tahun, ketika ruang itu mulai mapan dan fasilitas tersedia, idealisme yang dulu mengikat mulai melemah. Mereka tidak lagi berjuang bersama melawan kelangkaan; mereka mulai bernegosiasi atas kenyamanan.
Solidaritas berubah menjadi ketergantungan moral. Yang dulu disebut gotong-royong kini bergeser menjadi pembenaran untuk tidak bekerja keras:
“Kita semua setara, jadi tak perlu ada hierarki.”
Yang dulu dimaknai sebagai kepercayaan berubah menjadi kelonggaran:
“Kita saling memahami, jadi tak perlu disiplin.”
Dan yang dulu dimulai sebagai gerakan belajar bersama, kini menjadi tempat berlindung bagi mereka yang takut diuji dunia luar.
Pada titik ini, nilai-nilai luhur seperti kolektivitas dan kesederhanaan kehilangan dimensi etisnya. Ia menjadi alat pembenaran stagnasi.
Manusia adalah makhluk adaptif, tetapi juga rasionalisasi terbaik bagi kemalasannya sendiri. Dalam konteks komunitas kreatif, banyak anggota yang meyakini bahwa “tidak mencari uang” adalah bentuk kemurnian moral, padahal di balik itu tersembunyi ketidakmampuan mengelola tanggung jawab. Mereka lupa bahwa etos non-profit bukan berarti bebas dari etika profesional.
Yuval Noah Harari pernah menulis bahwa yang membedakan Homo sapiens dari spesies lain bukan hanya kemampuan berimajinasi, tetapi kemampuan berimajinasi bersama. Kita bisa menciptakan fiksi kolektif seperti “negara”, “agama”, atau “komunitas kreatif” — dan percaya padanya seolah nyata. Namun di saat fiksi itu tidak lagi dihidupi oleh tindakan nyata, ia berubah menjadi ritual kosong. Kita bisa terus berbicara tentang “semangat awal”, “tujuan bersama”, atau “keluarga besar”, padahal di bawah permukaannya hanya tersisa rutinitas tanpa produktivitas.
Inilah tahap kedua dalam rantai kegagalan sosial: ketika nilai-nilai yang dulu menyelamatkan sistem, kini justru menghambatnya berevolusi.
Antropologi mengenal fenomena serupa dalam masyarakat pasca-kolonial. Banyak negara yang merdeka dengan idealisme anti-imperial justru gagal membangun sistem pemerintahan modern karena terlalu lama hidup dalam narasi perjuangan. Para pemimpinnya tetap berbicara tentang “perlawanan” bahkan setelah mereka sendiri menjadi penguasa. Mereka lupa bahwa menjaga kemerdekaan membutuhkan bentuk baru dari perjuangan — bukan lagi melawan penjajah, tetapi melawan kemalasan dan ketidakefisienan internal.
Begitu pula dalam organisasi modern. Ketika komunitas yang dulunya menentang sistem akhirnya menjadi bagian dari sistem, mereka harus berani mengubah bahasa moralnya. Jika tidak, solidaritas berubah menjadi nostalgia; nostalgia menjadi penghalang; dan penghalang menjadi alasan kegagalan.
Kita sering mengira kegagalan terjadi karena kurangnya dana, koneksi, atau bakat. Tapi sebenarnya, sebagian besar kegagalan sosial berasal dari ketidakseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan tanpa tanggung jawab melahirkan anarki lembut — bentuk di mana semua orang merasa punya suara, tapi tak ada yang mau bekerja. Dan tanggung jawab tanpa kebebasan melahirkan birokrasi — struktur yang rapi tapi mati rasa.
Di antara dua kutub itulah komunitas modern sering terjebak: terlalu bebas untuk disiplin, terlalu takut untuk menjadi profesional.
Jika kita kembali ke kerangka Freakonomics, stagnasi semacam ini adalah rantai kegagalan mikro: satu orang tidak menyelesaikan tugasnya; orang lain tidak menegur karena takut konflik; koordinasi memburuk; kepercayaan berkurang; dan akhirnya sistem berhenti berfungsi. Tak ada ledakan, tak ada bencana besar — hanya erosi perlahan dari kepercayaan dan kompetensi.
Namun tidak semua stagnasi harus berakhir dengan kehancuran. Dalam sejarah, ada fase di mana masyarakat berhasil keluar dari kebuntuan dengan cara mengganti mitosnya. Eropa abad ke-18, misalnya, mengganti mitos teologis dengan mitos rasionalitas. Gerakan koperasi pada abad ke-19 mengganti mitos kapitalisme individual dengan solidaritas produktif. Dan revolusi digital pada abad ke-20 mengganti mitos industri dengan inovasi dan kolaborasi global. Setiap kebangkitan besar dimulai ketika manusia berani mengubah narasi tentang dirinya sendiri.
Artinya, ketika sebuah komunitas modern gagal, bukan karena para anggotanya jahat, malas, atau bodoh — tetapi karena cerita lama yang dulu mempersatukan mereka tidak lagi relevan. Dan di sinilah dilema paling tragis muncul: mereka mencintai cerita itu terlalu dalam untuk melepaskannya. Tapi, seandainya pun sebuah komunitas modern bisa berkembang menjadi korporasi mapan, kegagalannya juga bisa lebih parah.
Bersambung ke bagian III: Rantai Kegagalan: Evolusi Moral yang Mandek. Terbit Senin.
Terima kasih telah membaca sampai habis. Website ini jalan dengan sumbangan, iklannya tak menghasilkan, dengan lisensi Creative Commons, Atribution, Non commercial. Kamu boleh pakai konten ini selama memberikan link sumber dan bukan untuk tujuan komersial. Kalau kamu suka dengan yang kamu baca, silahkan traktir saya kopi murah.
Berlangganan
Masukan email kamu untuk dapatkan update. Gratis.