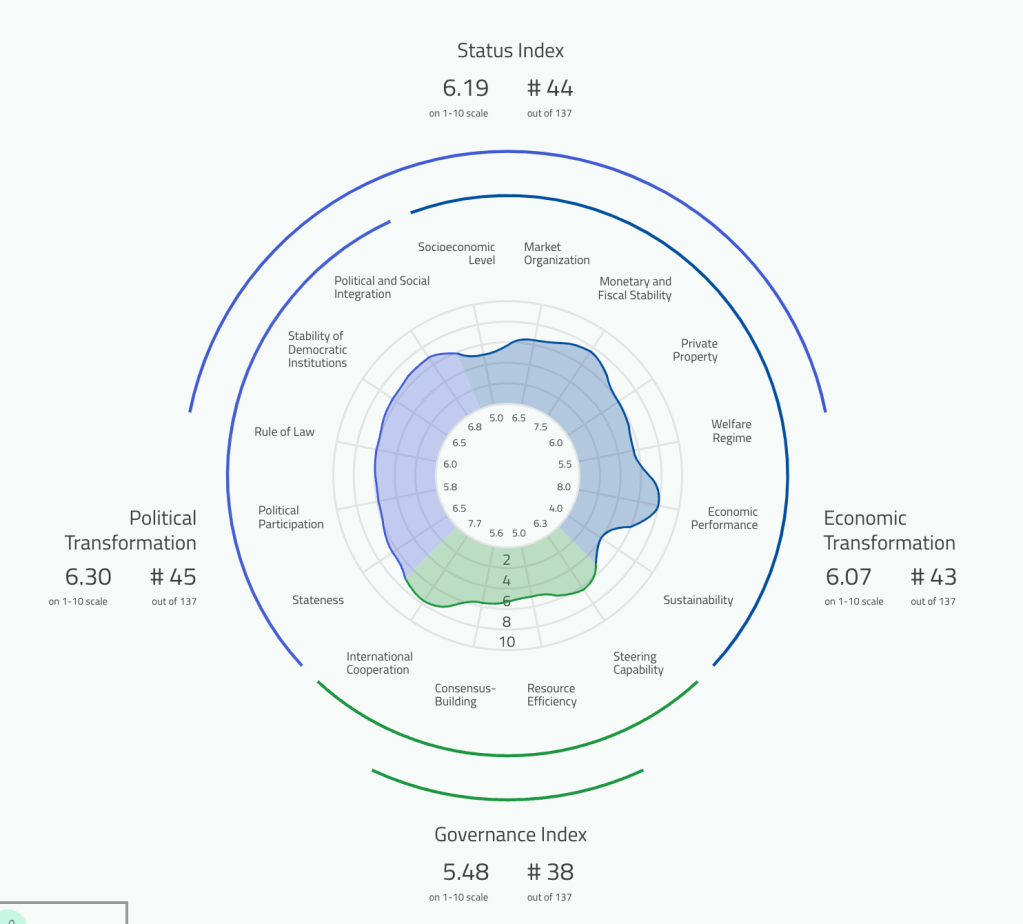Saat sudah muak melihat sosial media, sudah lelah membaca dan bekerja, sudah capek berdebat, mungkin ini saatnya menulis racauan. Halo kawan-kawan pembaca yang budiman semoga tidak sujatmiko. Karena integritas adalah hal yang paling kita butuhkan hari-hari ini.
Kita bisa lihat tuntutan 17+8 tidak berjalan dengan baik tanggapannya. Waktu ini ditulis, baru 3 tuntutan yang ditanggapi dengan tindakan. Tak ada maaf dari presiden karena ia merasa tidak salah informasi atau salah mengangkat orang atau salah kebijakan.
Lalu Nadiem Makarim ditangkap korupsi–yang saya yakin seperti Tom Lembong, tidak mengandung mens rea. Di Thread saya diajak ribut beberapa guru atau orang tua murid yang benci sekali sama mas Nadiem dari mulai soal penghapusan UN, hingga soal zonasi.
Saya sih paham mas menteri kemarin itu maunya apa, dan saya bias sih mendukung beliau, karena saya pendidik yang pendidikannya tinggi, sudah belajar critical pedagogy, dan pernah ngajar di sekolah-sekolah mahal. Tentunya jadi debat kusir ketika bicara dengan guru entah dari mana yang bilang “Gadget tidak ada hubungan dengan kurikulum,” atau “tanpa kompetisi murid tidak bisa pintar, kurang motivasi.”
Ini orang-orang yang salah paham dan terbawa doktrin pendidikan orde baru. Tapi saya malas ribut, maka di sini saja, di website saya sendiri saya akan jelaskan.
Pertama soal UN. Saya pernah dapat project bikin UN waktu kuliah. Waktu kuliah, guys! Belum lulus! Disuruh bikin soal UN dengan goreng-goreng sal tryout gitu. Dibayar 5 juta, dan nama saya tidak masuk ke tim penulisan juga (yang isinya Drs, Dr, prof) whatever. Gak saya ambil kok. Bau pesing. Terus saya ingat polemik menteri waktu itu bahkan bikin standard UN karena dapet bisikan waktu Umroh apa. Ghokil.
Selain itu soal kompetisi. Ujian itu harusnya bahan assesmen guru dan sekolahnya, untuk mengetes kemampuan pendidik, bukan kemampuan peserta didik! Kalau siswa nilainya jatuh, atau tidak lulus, siswa itu harus jadi pusat perhatian untum diteliti, dicari cara ajarnya biar lulus, dan dievaluasi cara mendidiknya, biar bisa diperbaiki terus sistem pendidikannya. Bukan malah marah-marah ketika muridnya bodoh, bodoh!
Ini juga menyangkut zonasi. Dulu ada sekolah unggulan, sekolah rendahan, buat apa itu? Kompetisi lagi? Bangga-banggaan anak masuk negeri atau swasta? Tambah gagal dong, sistem kayak gitu mempermalukan sekolahnya. Kalau anaknya masuknya pintar keluarnya pintar, lalu apa kerjaan sekolah? Harusnya masuknya bodoh keluarnya pintar. Masuknya pintar keluarnya bijaksana.
Terus ada yang mengeluh, “Murid saya kelas 1 SMP belom bisa baca. Kok bisa masuk SMP?”
Saya tanya, bisa pake gadget nggak? Dia jawab bisa. Lah bisa baca dong! Terus dia bilang ada bapak-bapak tetangganya bodoh tapi bisa pake HP. Iya bisa baca dong pak gurru!!!
Mungkin depan bapak aja malas ketahuan bisa baca nanti dikasih PR. Haha.
Dia nanya, “Apa hubungannya Gadget dengan kurikulum?”
Bapak guru, gadget itu guru mutakhir, lebih canggih dari bapak. Karena dia punya UI/UX yang ngajarin orang make gadget tanpa frontal diajarin gadget. User Interface artinya tampilannya menarik. User experience artinya pengalamannya asik. Dua-duanya syarat ngajar yang penting. Mungkin bapak UI/UX nya masih sistem DOS atau windows 3.11. Keren pada jamannya.
Lagian bikin kurikulum dan LMS sekarang kan udah pake gadget semua pak. Ampun! Saya ini yang salah. Saya bias.
Banyak guru seperti bapak itu, banyak murid yang akan jadi bodoh karena Nadiem Makarim berusaha bongkar-bongkar sistemnya yang sudah lama sekali bobrok. Ya buat saya, Nadiem adalah awal untuk membuka satu persatu masalah pendidikan kita. Bahwa masalah itu ada dan harus kita tanggulangi.
Ah, jadi panjang racauan ini. Tapi sudah lah. Minimal saya jadi tak usah balas thread saya yang sedang viral itu. Bangsat lah.
Ini silahkan kalau mau cek sendiri polemiknya. Sa mau tidur saja.
Thread:
Menurut gue sebagai pendidik dan yang pernah tahu bagaimana cara kementrian sebelom mas Nadiem bikin Ujian Nasional (pake wangsit anjir), Nadiem Makarim adalah salah satu menteri pendidikan terkeren sepanjang sejarah negeri ini.
Kementrian pendidikan separah itu selama ini, maka harus banget diobok-obok. Di jaman Nadiem jauh lebih jelas permasalahan dan usahanya untuk mengejar ketinggalan.