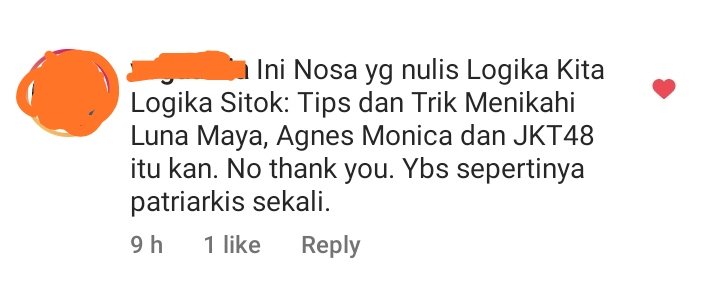Semua orang tua bersalah pada anaknya, dan setiap kesalahan akan membekas buat si anak dari kecil hingga ia dewasa. Orang tua yang baik adalah orang tua yang dapat mengevaluasi diri dan terus berusaha meminimalisir kesalahan terhadap anak. Tapi ketika kita bicara masalah parenting, kita tidak cuma bicara soal keluarga atau masalah individual, kita juga harus bicara tentang negara dan kebudayaan secara luas, tentang bahasa, dan juga tentang konsepsi pendidikan terhadap anak.
Hari ini kita sudah setuju soal buruknya konsep perpeloncoan atau kekerasan fisik dan verbal terhadap anak–walau banyak juga orang tua konservatif yang meneruskan lingkaran kekerasan itu, tapi kebanyakan orang tua terdidik yang punya akses ke internet sudah tidak begitu lagi. Namun kita tidak bicara soal tempat-tempat yang jauh dari pusat informasi. Kita tidak bicara dalam konteks kampung kota, kampung, atau desa. Kita sulit melihat seperti apa informasi utama yang ada di lapangan, apalagi soal kekerasan terhadap anak.
Sebagai seorang penonton film, filmmaker, dan peneliti saya selalu tertarik dengan film-film kejahatan, dan beberapa tahun terakhir saya menonton beberapa film soal kekerasan anak terkini. Banyak sekali film yang mengangkat hal ini, dan setiap film, diskusi, dan aktivisme dapat membantu membuat dunia lebih baik untuk anak-anak dan masa depan negara kita. Ini adalah beberapa contohnya.
The Trials of Gabriel Fernandez, seperti judulnya, bercerita tentang persidangan orang tua Gabriel (ibu dan ayah tirinya) yang menyiksa Gabriel sampai meninggal. Settingnya di California, dan dari persidangannya terbukalah sebuah ketidakbecusan departemen sosial di Amerika Serikat, yang telah berkali-kali menerima laporan soal Gabriel yang sudah luka-luka, namun selalu mandeg di birokrasi sampai anak itu meninggal. Parahnya departemen sosial ini seperti dijawab oleh serial dari belahan dunia lain, The Chestnut Man.
Setting The Chestnut Man ada di Denmark dan perbatasan dengan Jerman. Ceritanya soal seorang pembunuh berantai sadis yang modus operandinya (1) melaporkan orang tua anak yang ditelantarkan ke Departemen Sosial, dan (2) jika tidak digubris, maka orang tua anak itu akan dibunuh dan anggota tubuhnya dimutilasi, serta dibuat seperti chestnut man (mainan orang-orangan dari kulit kacang kastanyet.)
Yang paling menarik adalah, salah satu tokoh kunci yang membuat seluruh pembunuhan ini mungkin adalah seorang perempuan yang menjabat sebagai Menteri Sosial di Denmark. Film ini secara harfiah menyalahkan dan membawa struktur besar negara, sebagai penyebab utama kenapa kejadian ini berlangsung, dan pelakunya sudah pasti dan jadi bukan spoiler, adalah korban kekerasan anak ketika ia masih kecil. Plot yang sama seperti Pintu Terlarangnya Joko Anwar.
Di Indonesia sendiri, laporan kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat tahun demi tahun. Kompas melansir bahwa tahun ada kenaikan dari 11.057 kasus di tahun 2019 menjadi 14.517 kasus di tahun 2021 (Kompas.com, 20 Januari 2021). Ini juga disebabkan institusi kepolisian yang lebih sibuk menjaga nama daripada bekerja menyelesaikan kasus, seperti laporan mendalam yang ditulis project Multatuli Tanggal 6 Oktober 2021. Dalam artikel berjudul “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan.” Tiga anak ibu Lydia (nama samaran) itu diperkosa oleh mantan suaminya. Si ibu lapor ke dinas sosial dan polisi, yang justru mempertemukan anak-anaknya dengan si pelaku. Semua tambah runyam karena polisi dan dinas sosial sama sekali tidak mengerti bagaimana caranya menangani sebuah kasus kekerasan seksual kepada anak. Akal sehat saja mereka tidak punya.
Memang, belum tentu anak-anak yang dilecehkan ini akan jadi penjahat, atau akan melecehkan orang lain. Tapi yang pasti traumanya akan keras, mereka akan memiliki hidup yang sulit, disabilitas psikososial. Ini masalah besar yang pemecahannya hanya bisa dengan kebijakan-kebijakan yang jalan beriringan dari banyak arah: secara undang-undang, hukuman harus diperberat; laporan harus dipermudah; dan yang paling penting, mengakui kesalahan dan aparat serta penjabat publik semua harus dididik ulang soal pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, dan bagaimana cara menangani korban. SOP harus sangat jelas.
Satu kasus lagi yang menyeramkan adalah seorang ibu yang menggorok anaknya. Ini kejadian yang sudah terjadi berkali-kali terhadap ibu yang stres. Dalam film kita bisa melihatnya di film The Others besutan Alejandro Amenabar. Di situ kita melihat tokoh ibu yang dimainkan Nicole Kidman yang membunuh anak-anaknya karena stres trauma perang.
Di kejadian nyata, pembunuhan anak oleh orang tua selalu terjadi karena masalah struktural (ekonomi, ideologi politik dan perang.) Hitler dan pengikutnya pun membunuh anak-anak mereka karena kalah perang, atau bunuh diri masal di Jonestown, atau bom bunuh diri anak, karena agama dan ketidakpuasan politik-ekonomi.
Dari sini kesimpulan utamanya adalah: tidak ada orang tua waras yang membunuh anak-anaknya karena motivasi pribadi. Semua karena motivasi struktural bahwa dunia yang mereka hidupi memang tidak mendukung anak-anak untuk tumbuh berkembang. Jadi terngiang kata-kata eksistensialis Soe Hok Gie: Yang paling beruntung adalah yang tidak dilahirkan, yang beruntung kedua adalah yang mati muda, dan yang paling sial adalah mati tua—karena kehidupan dalam masyakarat yang sakit akan berkutat pada penderitaan.
Masa depan kita suram dengan banyaknya anak-anak yang dilecehkan seperti ini, perjuangan tetap kenceng, rekomendasi, petisi terus berjalan walau gaungnya seringkali kalah dengan isu-isu lain. Yang kita bisa lakukan hari ini adalah mendidik dan menyebarkan informasi yang objektif, saintifik, dan bertindak tegas ketika kita melihat kekerasan seksual, apalagi terhadap anak. Ketegasan dimulai dari hukuman sosial hingga legal. Dan kalau legalnya tidak kuat, kita bisa memakai media untuk berkoar, ajak wartawan, blogger, tweeps, semua untuk marah dan mengkoreksi, memberikan tekanan penting terhadap kebudayaan dan negara kita. Komnas Perempuan juga meluncurkan catatan tahunan yang penting buat kita lihat sebagai salah satu cara mengawal agar jaminan hukum dan sosial bisa berjalan dengan baik di negeri kita, untuk mencegah Trials of Gabriel Fernandez atau pembunuhan The Chestnut Man di Indonesia.