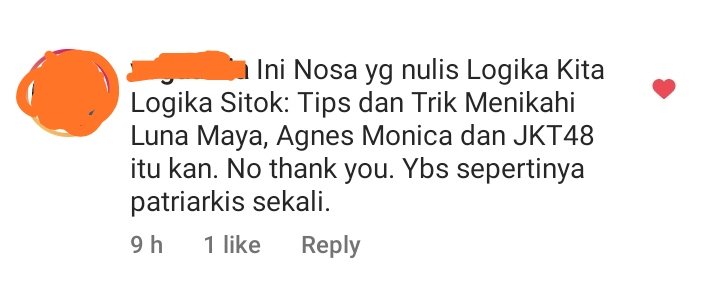Awalnya tulisan ini dibuat bersama dengan ChatGPT, jadi semacam metodologi penulisan baru. Tapi setelah beberapa kali dilihat, ternyata belum ada AI yang bisa mengejawantahkan ide-ide liar di kepala gue. Jadi ini adalah hasil dari menulis ulang esei ini.
3 Body Problem, series Netflix yang dibikin sama orang-orang dibalik Game of Thrones punya ide yang lumayan segar khususnya soal science fiction alien yang gabungin antara game, teori fisika, dan kritik sosial humanis. Gue tertarik bahas ini karena udah lama nggak nonton series yang gayanya jejepangan kayak gini. Yes, menurut gue film ini stylenya jepang banget. Bisa banget jadi anime. Tulisan ini akan bicara lewat jalur paling malas dalam kritikf film: penceritaan. Yang akan lo baca punya posisi lebih rendah dari review. Anggaplah ini genre tulisan kesukaan gue: racauan. Gue akan bahas 3 Body Problem secara tematis, dari masalah kritik terhadap developmentalisme dan alam, kritik terhadap ideologi dan agama, dan penjabaran soal altruisme dan kemanusiaan.
Developmentalisme dan alam
Jadi hari-hari ini gue tergoda sekali untuk pake AI, dari mulai mencari makanan di HP, sampai model bahasa di copilot, open AI, editing video audio, bikin gambar di dall e dan canva, sampai di wordpress yang sedang kalian baca ini. Ini semua adalah perkembangan manusia, dan AI menjadi satu lagi loncatan peradaban, setelah penemuan mesin uap industri di hampir 200 tahun yang lalu yang membuat industrialisasi dan loncatan peradaban: mesin dan perang, lalu industrialisasi dalam ekonomi global. Setiap loncatan dan percepatan peradaban ini efeknya lumayan buruk untuk tempat tinggal kita sendiri. Tapi gue nggak akan bilang bahwa manusia merusak alam atau merusak bumi. Alam tidak rusak atau baik, alam sederhananya adalah keberadaan yang punya jalannya sendiri dan keputusannya absolut, kita semua cuma numpang. Ini adalah bahasan utamanya: 3 Body Problem dimulai dengan usaha untuk menghentikan perkembangan teknologi, pembunuhan para ilmuan yang berpotensi untuk melawan para alien, atau mempercepat kerusakan planet yang ingin dituju para alien ini 400 tahun lagi. Ini masuk akal sekali ketika kita lihat, dalam rentang waktu 200 ribu tahun manusia hidup, kita cuma perlu 200 tahun lebih sedikit untuk bikin planet kita tidak lagi bisa kita tinggali. Dengan pengakuan bahwa kita cerdas, dalam jumlah besar kita benar-benar spesies yang tolol karena sedang pelan-pelan bunuh diri. Dalam 400 tahun, tidak akan ada lagi keseimbangan untuk menopang kehidupan, dan para Alien yang notabene lebih cerdas dari kita, khawatir.
Ideologi dan agama
3 Body Problems, atau dalam terjemahan kerennya, Trisurya, adalah konsep trias yang sering kita pakai. Di struktur cerita ada tiga babak, di agama ada tiga dewa atau tuhan utama, di politik ada trias politica, ini semua jadi masalah besar yang dialami ras alien yang planetnya ada tiga matahari. Mereka mengulang peradaban dengan kiamat yang berkali-kali dalam jangka waktu yang jauh lebih lama dari kita, karena planet dengan tiga matahari, tidak pernah bemar-benar stabil. Seperti sistem trias yang kita anut, yang selalu mengandung tesis, anti-tesis dan sintesis, selalu ada yang diciptakan, dipelihara, lalu dihancurkan.
Gue suka banget kritik terhadap agama dan politik di 3 Body Problem. Ketika alien dengan kekuatan omnipoten Tuhan berjanji akan datang, manusia panik dan terbagi antara mereka yang skeptis yaitu golongan ilmuan, mereka yang menurut yaitu golongan agamawan, dan mereka yang melawan yaitu golongan politikus dan militer. Lagi-lagi, 3 Body Problem. Tentunya berhadapan dengan konflik, seringkali menghasilkan 3 outcome ini.
Dalam menghadapi pandemi, sebagai contoh. Agama mengajarkan doa dan pasrah menunggu, sains berusaha memecahkan masalah tapi butuh dukungan uang dan politik, dan politik sibuk ribut antar sesama, sehingga masalah jadi berlarut-larut. 3 Body Problem merefleksikan sebuah solusi terhadap ketidaksinkronan trias ini: kembalinya kediktatoran yang diceritakan dengan PBB memberikan status absolut untuk tiga orang manusia yang boleh memerintahkan atau meminta apapun, tanpa harus menjelaskan apapun, karena Alien tahu segalanya kecuali isi pikiran orang. Pandemi kemarin pun cepat berakhir dengan munculnya berbagai diktator dan kebijakan ekonomi dan kesehatan yang dipercepat, diberi insentif steroid.
Altruisme dan kemanusiaan
Hal lain yang diperhatikan dari film ini adalah contoh-contoh persahabatan dan altruisme di antara tokoh-tokohnya. Jadi manusia itu terlepas dari keegoisannya masing-masing memiliki ikatan-ikatan sosial yang cukup kuat antar kinship atau persahabatan yang membuat cerita-cerita yang bermakna tentang keberadaan manusia yang sebenarnya sangat pendek dalam umur semesta ini. Maka dari itu gue pikir film ini pada akhirnya adalah film tentang kemanusiaan dan tentang pengorbanan yang masih berjalan hingga hari ini bahwa banyak orang-orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan dalam bentuk pengorbanan itu terlepas dari hasilnya nantinya akan seperti apa toh ketika dilakukan sebuah pengorbanan adalah murni keberanian untuk menjadi baik.

Secara estetika series ini punya kualitas yang tinggi aktor-aktor yang kuat dan meyakinkan tentunya. Karena bagaimanapun ini film Netflix dengan modal yang besar. Ada satu hal yang mengganjal buat gue yaitu tentang bagaimana eksklusifnya sebuah modal untuk membuat film atau seri yang sifatnya global. Terlepas dari ceritanya yang sangat peduli pada kemanusiaan dan alam dan ilmu pengetahuan tetap saja produksi film ini menghabiskan banyak dana dan sumber daya yang sangat eksklusif untuk kelas-kelas tertentu. Ini yang lumayan mengganggu gue sebagai seorang filmmaker, bahwasanya seringkali film mengeksploitasi kebudayaan dan kepercayaan kemanusiaan tapi di saat yang sama film ini dirayakan dalam bentuk-bentuk penghabisan dana dan sumber daya serta ketidakadilan sosial untuk membuat filmnya. Semua jadi serba ironis. Ada 3 body problem dalam film making yaitu budget, timeline, dan ide. Untuk membuat sebuah karya yang monumental diperlukan waktu yang panjang, budget yang sangat besar dan ide yang baik. Hampir semua film-film atau seri-seri dengan budget yang besar, timeline yang panjang dan ide yang spektakuler itu tidak efektif karena bicara soal harga dan ekonomi kita bicara tentang psikologi manusia yang sebenarnya tidak bisa dipercaya.
Di sini juga membuat gue seringkali berpikir tentang apa yang harusnya dilakukan untuk bertahan supaya spesies kita ini tidak bunuh diri pelan-pelan seperti yang sering kita bicarakan lewat kapitalisme dan perusakan alam dan eksploitasi sumber dayanya. Tapi ini semua cuma perenungan yang gua harap bisa dibicarakan dan didiskusikan sama-sama supaya ke depannya film akan jauh lebih inklusif atau bahkan sederhana menjadi medium yang bisa dibuat semua orang menggunakan AI. Dari situlah kita kembali berbagi cerita. Karena untuk AI cerita hanya data sementara untuk kita, cerita adalah menjadi manusia.
Terima kasih telah membaca sampai habis. Website ini jalan dengan sumbangan, iklannya tak menghasilkan, dengan lisensi Creative Commons, Atribution, Non commercial. Kamu boleh pakai konten ini selama memberikan link sumber dan bukan untuk tujuan komersial. Kalau kamu suka dengan yang kamu baca, silahkan traktir saya kopi murah.