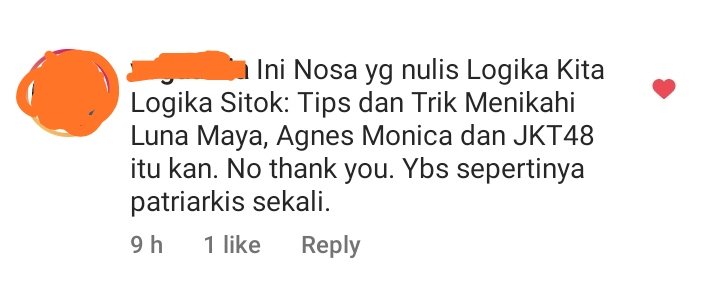Setelah kerja di industri media sejak tahun 2005, saya memutuskan untuk fokus ke pendidikan soal film dengan basis produksi–artinya saya akan bikin film sambil belajar dan mendidik sampai saya mati. Dari film-film kita yang bikin “Indonesian Fever” di berbagai festival internasional dunia, kita bisa melihat bangsa kita berkembang. Padahal ini baru di tahap di mana masyarakatnya belum semaju itu. Ada yang keracunan MBG, ada orang hilang lagi, tapi banyak film bagus yang terjadi, dengan dana yang sebenarnya nggak bisa dibandingin sama Korea Selatan apalagi Holywood, namun penceritaan, teknis dan kolaborasinya punya bentuk-bentuk yang keren.
Yang Diceritakan dan Yang Dilarang
Cerita sebuah bangsa tidak hanya soal kisah apa yang ditulis, tetapi juga kisah apa yang dilarang. Film selalu berhadapan dengan batas: apa yang boleh, apa yang tabu, apa yang harus disamarkan dalam simbol. Di Iran, sutradara menyelipkan kritik sosial lewat metafora anak kecil atau perjalanan sehari-hari. Di Cina daratan, penyensoran bekerja bahkan sebelum kamera dinyalakan—sejak praproduksi naskah. Larangan inilah yang sering justru memunculkan lapisan artistik yang canggih: bagaimana menyampaikan hal-hal yang tidak boleh diucapkan dengan bahasa visual dan sinematik.
Indonesia tidak seketat itu dalam hal sensor ideologis, tapi problemnya lain: cerita sering tunduk pada selera pasar. Yang laku diulang, yang menantang pasar jarang diberi kesempatan layar. Maka industri lebih sering mengikuti, ketimbang membentuk.
Teknologi: Siapa yang Punya Akses?
Film juga adalah soal teknologi. Kamera, lensa, perangkat editing, hingga efek visual. Teknologi menentukan standar estetika global: bagaimana sebuah gambar dianggap “cinematic,” bagaimana suara terdengar “bersih.” Pertanyaan pentingnya: siapa yang punya akses?
Negara besar menyediakan teknologi mutakhir bagi para filmmaker mereka. Negara berkembang sering hanya bisa mengejar, atau menambal dengan kreativitas. Ada film-film Indonesia yang secara teknis bisa menyamai standar Hollywood—jernih, presisi, mahal. Tapi jumlahnya masih terbatas, dan sering kali hanya terjadi karena adanya sokongan finansial ekstra, bukan karena sistem yang terbangun.
Kolaborasi Adalah Ruwet
Sisi paling krusial justru ada di sini: kolaborasi. Film adalah kerja kolektif. Tidak ada film yang lahir dari satu orang saja, meski nama sutradara sering dikultuskan. Di balik satu film, ada ratusan, bahkan ribuan negosiasi: sutradara dengan produser, penulis dengan aktor, kru dengan investor, pekerja lapangan dengan birokrasi perizinan.
Di negara dengan sistem produksi rapih, kolaborasi ini terasa militan: disiplin, efisien, tidak redundant. Tapi di banyak tempat, termasuk Indonesia, kolaborasi justru sering berantakan. Tidak ada standar yang konsisten, pendidikan film masih timpang, SOP longgar, regulasi tidak berpihak pada pekerja, dan struktur industri lebih sering diatur oleh kekuasaan informal ketimbang sistem formal.
Film sebagai Barang Mewah
Maka benar jika film adalah barang mewah. Ia hanya bisa lahir ketika ketiga sisi itu—cerita, teknologi, kolaborasi—bertemu dalam proporsi seimbang. Jika salah satu timpang, hasilnya akan terlihat. Film dari negara berkembang bisa saja kaya cerita dan kolaborasi, tapi teknologinya terbatas. Atau teknisnya sempurna, tapi ceritanya kosong karena tunduk pada pasar.
Indonesia punya potensi besar. Akses ke teknologi ada. Kreativitas cerita pun melimpah. Tapi tanpa keseimbangan yang serius—cerita yang berani bicara representasi, teknologi yang merata, serta kolaborasi yang terstruktur dengan SOP, pendidikan, dan dukungan legal—jangan harap industri ini bisa benar-benar maju.
Film adalah cermin peradaban. Kalau film kita masih berantakan, mungkin itu juga cermin dari bagaimana kita mengelola bangsa.