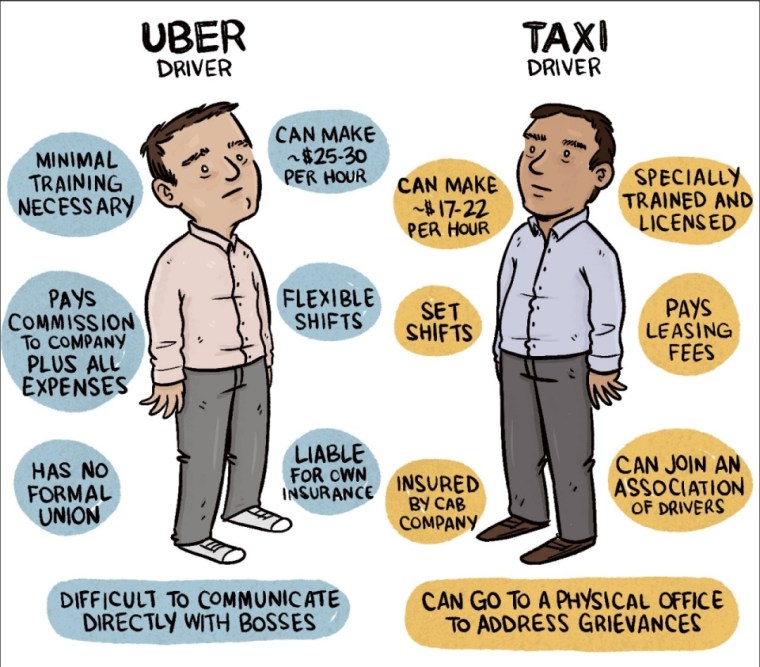Berikut adalah laporan 5 pementasan yang saya tonton di Amerika secara gratis. Gratis bukan berarti murahan, karena empat dari lima pementasan ini adalah profesional dan dimainkan oleh aktor-aktor kenamaan, dengan sutradara dan penulis yang kebanyakan menang Tony Award atau minimal masuk nominasinya. Hampir semua tiket pementasan ini didapatkan atas fasilitas Fulbright, jadi tulisan ini juga untuk berterima kasih atas akses ke kebudayaan tinggi Amerika.
William Shakespeare’s The Tempest (Central Park, May 2015)
Sutradara: Michael Greiff

Pementasan ini sangat lambat. Tempo tidak terbantu oleh musik ataupun bloking aktornya, padahal soal keaktoran pementasan di Central Park ini tidak main-main. Ada Sam Waterson, nominator Academy Award yang sering kita lihat dalam serial TV Newsroom dan Law and Order. Waterson bermain sebagai Prospero, namun seperti sama sekali tidak ada usaha untuk menghidupkan karakter yang berbeda dari dirinya sendiri.

Panggungnya begitu luas tapi kosong. Tata cahaya yang redup dan kalimat-kalimat Shakespeare yang sangat panjang tanpa dibantu musik yang mumpuni membuat pementasan Shakespeare in The Park tahun 2015 ini jadi salah satu yang bikin saya ngantuk. Apalagi aktor utama seperti Chris Parfetti yang bermain sebagai Ariel (asisten Prospero) benar-benar menjatuhkan tempo permainan. Gaya aktingnya yang agak ‘melambai’ seperti ingin memberikan karakter androgini di tokoh Ariel, alih-alih membuat pementasan kaya makna, malahan membuat intensitasnya jatuh bebas, karena semua kata dipukul rata dengan kelembutan.
Kostum dan treatmaent pementasan bertema Bondage dan Sadomasokisme. Tapi apa artinya tema itu jika dibawakan dengan energi dan nafsu yang rendah. Padahal seandainya ada usaha lebih, tema ini bisa membuat The Tempest jadi sangat aktual.

Vanya and Sonya and Masha and Spike
Sutradara: Aaron Posner/ Naskah: Christopher Durang

Salah satu pementasan terbaik yang saya tonton tahun kemarin, Vanya and Sonia and Masha and Spike benar-benar drama yang menggembirakan soal orang-orang menyedihkan. Adaptasi drama-drama Chekov oleh Christopher Durang ini diramu seperti sebuah lenong kontemporer yang sesuai perkembangan zaman. Uncle Vanya dibuat menjadi gay kesepian yang tinggal bersama Sonia, saudaranya yang perawan tua. Mereka didatangi adik bungsu mereka, Masha, seorang artis terkenal menjelang masa tuanya, yang membawa pacarnya, seorang berondong bernama Spike. Para aktor bermain sangat baik dalam format teater arena, yang membuat semua penonton tenggelam ke dalam konflik keluarga yang aneh ini.

Drama ini sungguh pantas memenangkan Tony Award 2013 sebagai drama terbaik. Kesederhanaan tata panggung dan jumlah aktor yang sedikit, membuat tidak ada satupun elemen drama ini yang terbuang percuma. Perasaan kesepian dan tawa naik-turun dengan sangat dinamis. Keseriusan yang dibangun bisa dipecahkan permainan, dan permainan dan tawa yang kita berikan bisa tiba-tiba membuat kita merasa bersalah karena ikut berbahagia di atas penderitaan orang lain.
Dear Evan Hansen
Sutradara: Michael Greiff/ Penulis Lirik dan Musik: Benj Pasek & Justin Paul

Memang kita tidak bisa menilai seseorang dengan satu karya saja. Saya bertemu kembali dengan karya Michael Greiff (yang tadi menyutradarai The Tempest di New York), di Washington DC. Kali ini ia menyutradarai sebuah drama musikal berjudul Dear Evan Hansen. Drama musikal remaja yang dbintangi oleh salah seorang bintang dari film Pitch Perfect 2, Ben Platt, meninggalkan kesan yang cukup dalam buat saya. Dari segi musik, drama ini luar biasa. Lagu-lagu gubahan Benj Pasek dan Justin Paul ini mengingatkan saya pada lagu-lagu Ben Folds Five, dan Ben Platt adalah vokalis yang sangat cocok membawakan lagu-lagu semacam ini. Anda bisa dengarkan lagunya di soundcloud yang saya cantumkan di bawah ini.

Saya pribadi kurang suka akting Ben Platt. Dia mungkin vokalis yang bagus, tapi begitu akting, ia seperti berusaha terlalu keras. Saya malah lebih suka akting Mike Faist, yang bermain sebagai tokoh Connor. Connor adalah seorang anak anti-sosial yang akhirnya bunuh diri karena depresi. Sepanjang drama ia menghantui Evan sang tokoh utama, yang memakai kematiannya sebagai alasan untuk kenal kepada Zoe, adiknya. Evan mendapat simpati banyak orang karena pura-pura jadi sahabat Connor, padahal sebenarnya itu semua bohong. Evan, seperti Connor adalah anak-anak anti-sosial, namun kematian Connor jadi pintu masuk Evan ke dunia pergaulan.

Dear Evan Hansen menjadi istimewa karena musik dan wacananya yang kontemporer. Liriknya yang dalam dan cerita tentang keterasingan remaja di era digital, benar-benar terasa aktual di masa ini, dimana semakin terkoneksi internet, seseorang menjadi tambah terasing. Terakhir, Michael Greiff memiliih tone warna tata panggung dan permainan visual yang sama seperti The Tempest: biru dan merah. Namun yang membuat Dear Evan Hansen menjadi sangat berbeda, adalah bagaimana desainer adegan, lighting, proyektor dan stage manajer membuat campuran antara visual digital dengan pergerakan material dari setiap layarnya. Pementasan ini tidak hanya menggunakan video mapping, tapi juga robot-robot panggung untuk memindah-mindahkan layar proyektor ke berbagai posisi dalam pergantian setting.
Midsummer Nights Dream
Sutradara: Ethan McSweeney

Sebagai aktor yang pernah memainkan drama “suka-suka” ini, sungguh tidak sulit buat saya memaparkan konsep dan konteksnya. Drama ini tidak logis dan memberikan kebebasan interpretasi yang sangat luas kepada sutradaranya. Teater Sastra UI, pernah mementaskan ini dengan menggabungkan kreativitas dan konsep suka-suka ini dengan maksimal, membiarkan setiap divisi dalam mengekplorasi dirinya masing-masing, dari mulai memasukan elemen tradisi dalam koregrafi dan tata gerak, pola-pola kain Indonesia dalam kostum, dan musik yang menggabungkan pop, rock dan tradisional. Pementasan oleh Shakespeare Theater Company ini tentu saja jauh lebih bermodal dan lebih mewah. Pemain-pemainnya pun bukan hanya mahasiswa atau anak muda, tetapi banyak pemain senior yang lebih berpengalaman. Namun dengan semua keunggulan itu, dengan sombong saya bisa bilang bahwa pementasan Teater Sastra UI tidak kalah kualitasnya.

Konsep yang ditawarkan McSweeney adalah penggabungan antara kenyataan yang hitam-putih dengan latar negara Eropa tahun 1930-1940an, dunia kelas bawah tempat para pemain drama rendahan seperti Bottom dan kawan-kawan yang berwarna coklat kusam, dan dunia peri dengan hutan imajiner di dalam sebuah panggung teater yang sudah rusak. Hutan imajiner ini menggunakan properti-properti panggung dari mulai tali tambang, piano rusak sebagai ranjang, ember dan lain-lain. Peri-peri menggunakan kostum zaman Victorian yang memang glamor dan penuh dengan mistisisme. Di satu sisi konsepnya jelas, namun di sisi lalu jadi terlalu jelas dan membunuh imajinasi penonton.

Pemeran Puck (Adam Green), yang nampaknya jadi aktor yang paling diistimewakan di drama ini, memang bermain prima. Bersama dengan peri-peri lainnya, ia memainkan atraksi lompat tali sirkus yang menantang. Aktor-aktor profesional ini bukan hanya terlatih akting, bernyanyi dan menari, tapi juga atraksi–sepertinya kebanyakan pementasan Midsummer Night’s Dream di industri teater memang harus menampilkan atraksi. Pementasan ini “aman” dan “pantas” untuk kelas Broadway. Tapi di saat yang sama jadi biasa saja, tidak banyak inovasi baru–karena saya pribadi sudah cukup riset dan mencari-cari model Midsummer Night’s Dream dua tahun lalu. Mungkin ini yang terbaik, karena toh, eksperimen yang terlalu macam-macam seperti yang dilakukan Julie Taymor bisa berakibat fatal.

Akeela and the Bee
Sutradara: Charles Randolph-Wright

Tidak banyak yang bisa saya katakan tentang Akeela and The Bee. Drama ini diangkat dari film anak-anak yang bertujuan membuat komunitas Afrika-Amerika yang lebih terdidik dan suka membaca. Dramanya pun dibuat oleh grup komunitas (campuran antara pemain profesional dan amatir). Kualitasnya kurang lebih sedikit di atas kebanyakan teater sekolah/kampus di Indonesia. Dan penontonnya pun rata-rata punya hubungan dengan komunitas tersebut.

Beberapa bagian drama ini cukup melelahkan saya, apalagi karena saya tidak akrab dengan aksen, istilah-istilah dan slang komunitas Afrika-Amerika. Walhasil, saya seringkali tidak tertawa ketika penonton terbahak-bahak, karena saya tidak bisa mengikuti dialog-dialognya. Drama ini mencoba menjadi multikultural, dengan menampulkan tokoh-tokoh berwajah Asia–khususnya Cina–dan memberikan mereka stereotipe “pekerja keras” yang memiliki orang tua yang “ambisius. Lucu juga sebenarnya, ketika orang kulit hitam banyak yang menuntut agar tidak distereotipe, drama ini sangat penuh stereotipe. Bukan hanya pada komunitas lain, tapi juga pada komunitasnya sendiri. Ironis.