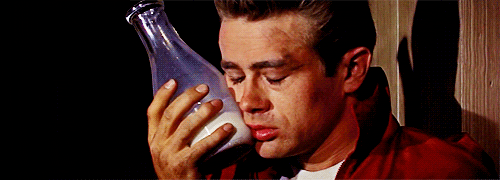Di tongkrongan MondiBlanc HQ, saya bertanya iseng:
“Kalau ide bisa diciptakan lebih dulu dari kenyataan, kenapa kita masih kayak gini-gini aja: perang, krisis, mana teknologi yang bisa mecahin itu?”
Pertanyaan itu sarkastik, tentu saja. Tapi seperti banyak ketidakjelasan pikiran saya, ini jadi pertanyaan yang bisa dibahas panjang.
Karena sejarah teknologi manusia, pada dasarnya, adalah rangkaian penundaan. Penundaan antara ide dan izin. Antara fiksi dan produksi massal. Dan yang paling menyedihkan: antara kesadaran kolektif dan kesiapan mental untuk bertanggung jawab atas konsekuensi ide-ide cemerlang itu sendiri.
Mari kita mulai dari atas: langit.
Dulu, manusia percaya bumi adalah pusat segalanya. Sampai Copernicus memutar balik semesta lewat De revolutionibus orbium coelestium di abad ke-16, dan Galileo mengkonfirmasi lewat teleskop murahan tapi revolusioner. Tapi perubahan itu tak terjadi seketika. Ide bahwa bumi hanyalah remah di antara putaran kosmis baru benar-benar diterima setelah ratusan tahun debat, ancaman, dan pembakaran buku. Fiksi kosmologis sudah ada jauh sebelum itu—di India kuno, di Yunani—tapi tanpa alat dan krisis, ia hanya dianggap dongeng.
Kita bisa lompat ke abad 19. Jules Verne menulis From the Earth to the Moon di tahun 1865, lengkap dengan deskripsi kapsul logam dan kalkulasi peluncuran. Tapi dunia baru benar-benar melihat manusia ke bulan pada 1969, dan itu pun karena Amerika panik kalah saing dari Uni Soviet. Lagi-lagi: fiksi menjadi nyata bukan karena dunia siap, tapi karena dunia takut.
Begitulah polanya: fiksi muncul saat dunia masih santai, dan jadi kenyataan saat dunia panik dan bingung.
Lihat mobil listrik. Sudah ada sejak 1800-an, tapi dikubur oleh bensin, ExxonMobil, dan budaya maskulin bertangki penuh. Lihat internet—yang awalnya imajinasi militer paranoid dalam bentuk ARPANET, lalu meledak jadi kebutuhan global karena kita terlalu malas mengangkat telepon.
Lihat pula video call yang muncul di film Metropolis tahun 1927, tapi baru kita pakai massal saat pandemi membuat bersalaman jadi aksi kriminal ringan.
Namun, ada satu fiksi yang belum juga jadi kenyataan: mesin waktu.
H.G. Wells menulis The Time Machine di 1895, dengan gagasan bahwa waktu adalah dimensi keempat yang bisa dilintasi. Teori relativitas Einstein di awal 1900-an diam-diam mendukung kemungkinan itu, dan matematikawan seperti Kurt Gödel bahkan menemukan solusi dalam persamaan ruang-waktu yang secara teori memungkinkan “closed timelike curves”. Tapi teori saja tidak cukup. Sebab ada yang lebih kuat dari sains: kekhawatiran etis.
Bayangkan jika seseorang bisa kembali ke masa lalu dan membisiki Adolf Hitler saat masih bocah: “Jangan ambil jurusan seni. Dunia akan berterima kasih.”
Atau sebaliknya—seseorang kembali dan mempercepat munculnya teknologi nuklir, hanya karena iseng.
Itulah paradoks. Dan inilah mengapa sains—meski kadang bisa melompat lebih cepat dari moral—akhirnya selalu ditarik kembali oleh ketakutan bahwa dunia belum siap menerima kenyataan yang bisa dibongkar pasang.
Di sinilah kita perlu menyebut Yuval Noah Harari, sejarawan Israel yang tak sengaja jadi semacam filsuf global. Lewat bukunya Homo Deus (2015), Harari menyodorkan spekulasi berani: bahwa manusia kelak akan naik level, bukan jadi makhluk spiritual, tapi makhluk teknospiritual. Ia membayangkan manusia dengan kapasitas ketuhanan—menguasai genetika, kehidupan, dan waktu. Ia menyebut mereka: Homo Deus.
Harari tidak sedang bercanda. Tapi ia juga tidak menulis nubuatan. Ia menulis sebagai seorang Yahudi sekuler yang hidup dalam negara yang secara politis selalu terlibat perang atas masa lalu. Dan justru karena itulah, ia sangat peka pada fakta bahwa: kekuasaan atas waktu, jika jatuh ke tangan yang salah, bisa mengulang sejarah dengan hasil yang lebih buruk.
Jadi jika kamu bertanya, kenapa sampai hari ini mesin waktu belum tersedia?, jawabannya bisa jadi bukan karena kita tidak bisa, tapi karena kita belum diizinkan oleh peradaban yang lebih sadar.
Mari kita berspekulasi. Mungkin di masa depan, umat manusia bukan lagi penguasa tunggal bumi. Mungkin kita hidup berdampingan dengan entitas baru—hasil kawin silang antara kecerdasan buatan, warisan trauma kolektif, dan kehausan spiritual yang belum sembuh. Mereka bukan dewa. Mereka hanya manusia yang belajar dari kesalahan dan memutuskan untuk tidak memberikan kekuatan absolut pada spesies yang masih panik kalau sinyal hilang satu bar.
Komite kosmik—sebut saja Komisi Kesadaran Temporal—dibentuk. Isinya bukan politisi, tapi entitas yang mampu menilai apakah sebuah masyarakat sudah cukup dewasa untuk tidak membunuh Hitler hanya demi konten TikTok.
Mereka menetapkan aturan:
“Mesin waktu akan dirilis saat umat manusia berhenti menyalahkan masa lalu dan mulai bertanggung jawab atas masa depan yang mereka bentuk sendiri.”
Maka, mesin waktu pun disimpan di luar jangkauan. Seperti senjata nuklir di laci anak-anak. Bukan karena ia tidak berguna, tapi karena kita belum siap memegangnya tanpa meledakkan diri sendiri.
Jadi jika hari ini kamu merasa punya ide cemerlang yang tak kunjung jadi kenyataan, ingat:
Realitas tidak menunggu siapa yang pertama berpikir, tapi siapa yang paling sadar dampaknya.
Dan jika suatu hari kamu ditawari kesempatan mengulang masa lalu, jangan tergoda.
Bisa jadi, satu-satunya alasan kamu ada di sini hari ini adalah karena semesta tidak memberi tombol undo.
Karena seperti yang diam-diam disepakati oleh para filsuf, insinyur, dan makhluk setengah dewa dari masa depan:
Kita tidak butuh mesin waktu untuk memperbaiki hidup, kita butuh keberanian untuk tidak lari dari hasilnya.