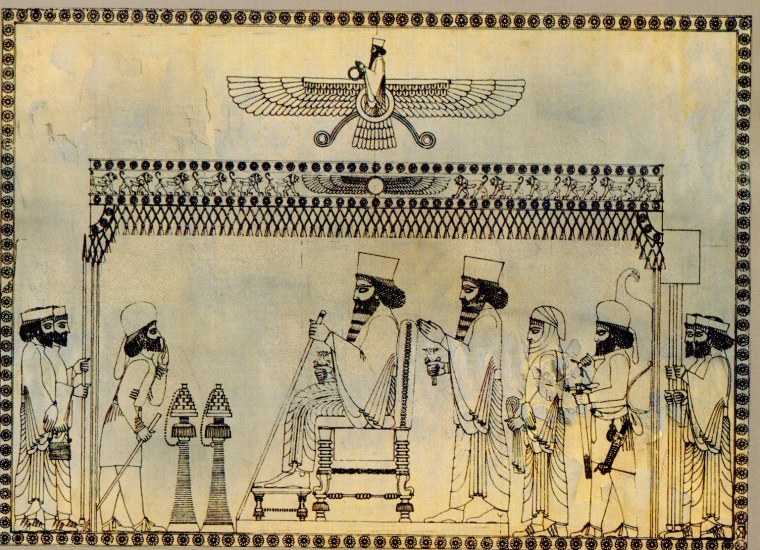Diterjemahkan tanpa izin dari tulisan Hilel Ofek, di jurnal The New Atlantic, no. 30 tahun 2011, halaman 3-23, Why The Arabic World Turned Away From Science.
Baca dari awal bagian I
Disclaimer penerjemah: Bagian-bagian terakhir dari terjemahan tulisan ini mengandung sedikit bias orientalisme dari penulis. Saya sendiri sebagai Muslim Indonesia, tidak setuju dengan beberapa hal yang dipaparkan penulis, namun demi semangat belajar dan kesetiaan terjemahan, saya akan menulis apa adanya. Saya tidak bertanggung jawab atas apa yang dipaparkan di sini, namun saya akan menulis sebuah kritik terhadap terjemahan ini setelah semua terjemahan ini selesai terbit. Saya harap ini juga bisa memicu diskusi lebih jauh yang berlandaskan fakta-fakta sejarah dan sumber primer yang logis dan berstandar akademik, sepeti teks asli Mr. Ofek. Gambar dan caption di blog ini adalah tanggung jawab penerjemah.

Standar Emas?
Dalam usaha menjelaskan kemunduran intelektual dunia Islam, penting untuk menunjuk beberapa faktor penting: otoritarianisme, pendidikan buruk, dan kurang dana (Negara Muslim menghabiskan dana pendidikan lebih rendah daripada riset dan pengembangan di negara berkembang, dalam presentase PNB-nya). Tapi alasan-alasan ini terlalu luas dan masih kasar, dan membuat lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di level yang lebih rendah, Islam mundur karena ia gagal untuk menawarkan cara untuk menginstitusionalisasi pemikiran bebas. Karenanya, ia gagal untuk menggabungkan antara iman dan rasio. Di banyak titik, masyarakat Islam lebih mundur bukan hanya dibanding dengan dunia Barat, tapi juga lebih mundur dari masyarakat Asia. Dengan beberapa negara pengecualian, setiap negara di Timur tengah yang menjadi bagian dunia Islam, dipimpin oleh otokrat, sekte Islam radikal, atau kepemimpinan suku. Islam tidak memiliki tradisi dalam memisahkan politik dan agama.
Kejatuhan peradaban Islam dan kemunculan peradaban Kristen adalah perkembangan yang memalukan untuk kaum Muslim. Karena Islam cenderung menempatkan kekuatan politiknya melalui klaim bahwa agamanya lebih tinggi dari agama lain, kemunduran kekuasaan duniawi Islam menimbulkan pertanyaan mendalam di mana kesalahan terjadi. Kurang lebih beberapa abad belakangan ini, banyak pembaharu Muslim berdebat, bagaimana cara mendapatkan kembali kehormatan yang hilang. Di periode yang sama, dunia Muslim mencoba, dan gagal, untuk membalik keadaan dengan meminjam teknologi Barat dan ide-ide sosial politiknya, termasuk soal sekularisme dan nasionalisme. Sebaliknya, rasa “modernisasi” ini justru membuat banyak Muslim jauh dari modernisasi. Ini menimbulkan pertanyaan baru: Dapatkah atau haruskah pencapaian Islam di masa lalu menjadi standar untuk Islam masa depan? Lagipula, sudah wajar untuk mengatakan, seperti yang Presiden Obama bilang, pengetahuan tentang sains Arab di zaman keemasan bisa bagaimana pun mendorong dunia Islam untuk berkembang sendiri, dan tidak begitu membenci Barat.
Cerita tentang sains Arab menawarkan jendela bagaimana hubungan antara Islam dan modernitas; mungkin juga, ia memegang prospek Islam kembali ke prinsip-prinsip yang ia sangat butuhkan untuk makmur, seperti persamaan hak antar gender, aturan hukum, dan kehidupan sipil yang bebas. Tapi kebanyakan orang Muslim hari ini lebih banyak berpikir bahwa kehidupan yang baik ditentukan dengan kembali kepada masa lalu yang murni dan saleh — dan bentuk ini terbukti beracun ketika berhadapan dengan modernitas. Islamisme, sebab utama kekerasan yang sering kita lihat di dunia sekarang sayangnya sangat dekat dengan sebuah doktrin yang ditandai nostalgia dalam pada era Islam klasik. Hingga hari ini, bilang bahwa al-Quran tidak setara dengan Allah bisa membuat orang dicap kafir.
Namun tetap saja, perkembangan intelektual dan keterbukaan budaya pernah terjadi di masyarakat Arab. Jadi sepanjang ingin melihat masa lalu, nostalgia salah yang fanatik bisa dijinakan. Beberapa Muslim pembaharu telah menunjukkan bahwa banyak Muslim di abad pertengahan menggunakan rasio dan ide modern sebelum masa modern, dan menggunakannya tidak berarti tidak saleh. Tidak juga berarti keduniawian mengalahkan akhirat. Di tataran intelektual, usaha ini bisa diperdalam dengan menantang ortodoksnya Ash’ari yang telah mendominasi Islam Suni selama seribu tahun — yaitu, dengan menanyakan apakah al-Ghazali dan kaum Ash’ari-nya benar-benar mengerti alam, teologi dan filsafat lebih baik daripada kaum Mu’tazilah.
Tetapi ada alasan-alasan kenapa dorongan untuk meniru nenek moyang Muslim, bisa jadi salah arah. Salah satunya, Islam abad pertengahan tidak menawarkan standar politik yang pantas. Jika dibandingan standar Barat, Sains Arab Zaman Keemasan Islam bukanlah Zaman Keemasan untuk Kesetaraan. Ketika Islam dibilang lumayan toleran dengan penganut agama lain, toleran hari ini berbeda dari toleran zaman Muslim (ataupun Kristen) awal. Seperti yang dikatakan Bernard Lewis dalan Yahudi dalam Islam (1984), memberikan hak yang sama kepada umat dan non-umat tidak hanya dilihat sebagai hal aneh, tapi juga “kelalaian dalam bertugas.” Yahudi dan Kristen adalah warga nomor dua dalam status sosiopolitis ketika awal zaman Muhammad, dan tekanan kekhalifahan Abbasid juga termasuk persekusi dan pemusnahan gereja dan sinagog. Zaman Keemasan juga era dimana perbudakan terhadap orang dengan kelas lebih rendah terjadi secara luas. Dengan semua pencapaian abad pertengahan Arab, cukup jelas bahwa sejarah sosial dan politisnya tidak bisa dipakai sebagai standar hari ini.
Namun ada banyak lagi alasan fundamental kenapa tidak masuk akal untuk menekan dunia Muslim agar kembali ke bagian masa lalunya yang menghargai rasio dan penelitian bebas; kembali ke masa Mu’tazilah tidaklah cukup. Bahkan aliran Islam yang paling rasional pun tidak pernah menekankan pentingnya rasio. Seperti yang dikatakan Ali A. Allawi dalan Krisis Peradaban Islam (2009), “Tidak ada aliran pikiran-bebas dalam Islam klasik — seperti Mu’tazilah — yang bisa menerima ide putusnya Allah-Manusia dan mengkritisi validitas al-Quran, walaupun mereka mendukung filsafat rasio.” Maka, di tahun 1889, akademisi Hungaria Ignaz Goldziher mencatat di eseinya “Perilaku Islam Ortodok kepada ‘sains kuno’” bahwa bukan hanya Ash’ari tapi juga Mu’tazilah yang “membuat banyak risalah polemik terhadap filsafat Aristotelian dan logika secara khusus.” Bahkan sebelum serangan al-Ghazali pada kaum Mu’tazilah, membaca filsafat Yunani tidaklah aman di luar kondisi tertentu, itu pun sifatnya sementara.
Tetapi yang lebih penting, mempopulerkan aliran rasionalis yang lama tidak akan mengajak orang Muslim lebih jauh dalam merefleksikan masalah teologi-politik Islam. Atas semua bantuan besar dalam menemukan kembali filsuf Arab yang berpengaruh (khususnya al-Farabi, Ibnu Rushid dan Musa bin Maimun/Maimonides) bisa menyediakan sebuah reinterpretasi Islam yang menantang prinsip pemerintahan komprehensif agama tersebut, dalam cara yang secara bersamaan meyakinkan orang Muslim bahwa mereka benar-benar kembali ke ajaran fundamental Islam ketika memakai sains dan filsafat. Karena belum ada ajaran di tradisi Islam yang bisa mengkritik agamanya sejauh Luther dan Calvin di Kristen.
Walaupun banyak hal yang kurang di dunia Islam, orang Muslim tetap bangga pada warisannya. Yang dibutuhkan justru mengurangi kebanggaan itu dan menambah kritik terhadap diri sendiri.
Ada alasan terpenting kenapa tidak perlu mendorong orang Muslim kembali ke masa lalunya: walaupun banyak hal yang kurang di dunia Islam, orang Muslim tetap bangga pada warisannya. Yang dibutuhkan justru mengurangi kebanggaan itu dan menambah kritik terhadap diri sendiri. Hari ini, kritik Muslim terhadap agamanya hanya dihargai sejauh ia bisa membuat orang Muslim lebih saleh dan rohaninya tidak korup. Dan kebanyakan kritik kaum Muslim adalah ke luar agama Islam, ke Barat. Praduga ini — apa yang disebut Fouad Ajami (merujuk dunia Arab) sebagai “sebuah tradisi politik untuk memerangi rasa rendah diri” — jelas jadi masalah utama Islam. Itu membuat segala informasi yang berlawanan dengan kepercayaan ortodoks jadi irrelevan, dan itu juga menutup debat ilmiah dan sejarah Islam sendiri.
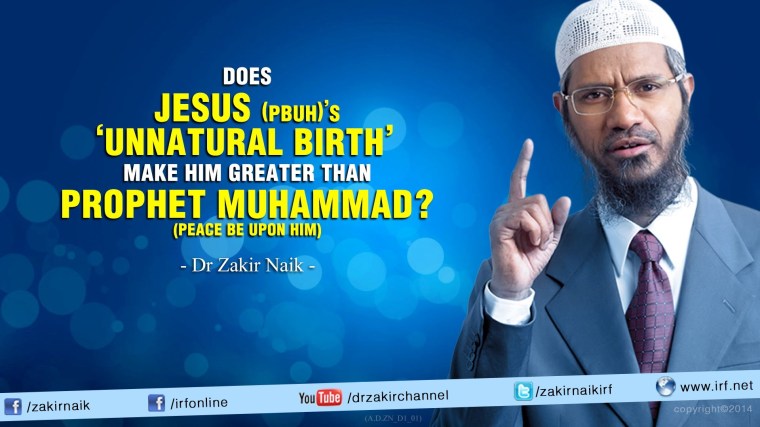
Dalam konteks ini, penelitian atas sejarah sains Arab, dan pemulihan serta riset manuskrip era itu, mungkin bisa memberikan keuntungan — selama dilakukan secara analitis. Artinya orang Muslim harus menggunakannya di dalam tradisi mereka sendiri untuk secara kritis berkenalan dengan kelemahan-kelemahan filosofi, politis, dan kesalahan yang ditemukan. Jika itu terjadi, perkembangan itu bukan karena usaha Barat, tapi akan jadi konsekuensi keinginan, kreatifitas, dan kebijaksaan kaum muslim sendiri –pendeknya, cara-cara itulah yang dipelajari Barat dari kaum Muslim di Zaman Keemasan.
Hillel Ofek adalah penulis yang tinggal di Texas, Amerika Serikat