
Seperti cepatnya perkembangan industri yang menyebabkan global warming dan perubahan iklim, jurang generasi 100 tahun terakhir ini semakin melebar. Apa itu jurang generasi? Jurang itu adalah perbedaan pengetahuan dan persepsi antar sekumpulang orang yang dipisahkan oleh satuan waktu lahir. Melebarnya jurang generasi, berbanding terbalik dengan jarak umur. Lebarnya jurang generasi artinya semakin hari, semakin sulit buat orang tua mengerti anak mudanya. Tapi menurut saya, ini cuma ilusi.

Coba saya jelaskan lebih jauh. Jurang generasi selalu ada di pikiran orang-orang yang merasa tua dan semakin hari semakin banyak orang yang ‘merasa tua’ tadi, karena peradaban sekarang jauh lebih cepat berubah daripada dulu dengan adanya internet dan majunya kecerdasan buatan. Tahun 50an, orang tua lebih mudah meneruskan nilai-nilai budaya pada anak. Namun pasca perang dunia kedua, semakin banyak “rebel without a cause,” khususnya di negara-negara demokrasi. “rebel without a cause” adalah ketidakmengertian orang tua pada anak yang memberontak, padahal yang tidak mereka mengerti bukan anaknya, tapi konteks sosial-politik-psikologi dimana anak itu hidup.
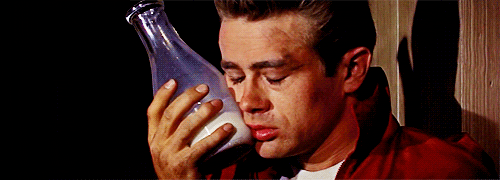
Sudah banyak pembahasan dan pelabelan generasi, dengan nama XYZ, atau baby boomer, post baby boomer dll. Pembahasan ini didasarkan pada event yang terjadi di sebuah masa yang mempengaruhi orang-orang yang lahir pada masa itu. Tapi buat saya, label itu telalu banyak dan membingungkan. Apalagi sulit ketika sample diambil dari negara tertentu. Waktu bisa jadi relatif secara geopolitik teknologi, buktinya saya kenal banyak orang yang lahir di tahun-tahun millenial, tapi otaknya setua senior-senior saya. Hahah.

Tapi semua orang angkatan saya ke atas, yang berhadapan dengan anak-anak muda sekarang–yaitu yang masuk dalam kategori milenial bukan hanya secara umur tapi juga secara perilaku hidup–memang banyak yang sedang bingung menghadapi generasi yang begitu cepatnya belajar, kritis, dan melompat melebihi apa yang pernah mereka bayangkan. Butuh energi muda dan akses informasi tak terbatas untuk menjadi seperti angkatan pemuda hari ini, saya sendiri jadi merasa tua di depan mereka yang dengan cepat bisa menguasai skill-skill baru.

Ketika saya pertama kali memegang kamera umur 20an, mereka sudah terekspos dunia video sejak SD. Ketika saya fasih berbahasa Inggris umur 16an, mereka sudah fasih dari balita. Tapi ini belum apa-apa. Di Amerika Serikat, saya menemukan bocah berumur 9 tahun yang baca bukunya lebih banyak dari saya: buku novel-novel petualangan tebal, dan sains fiksi macam-macam. Pulang dari Amerika, saya merasa bukan cuma saya yang ketinggalan: anak-anak muda yang sulit dimengerti orang tuanya di Indonesia, juga ketinggalan jauh dengan anak-anak muda di negara maju.

Artinya, mereka yang merasa ketinggalan oleh anak-anak muda Indonesia, bukan hanya tua tapi juga bodoh–termasuk saya.
Lalu kita yang tua mau apa? Ya, terserah. Mau belajar bersama yang muda, seperti yang saya lakukan ketika mengajar–yang mana sebenarnya saya belajar lebih banyak dari mereka daripada mereka dari saya; atau mau pakai senioritas, kemarahan, dan frustasi pada generasi yang mereka tidak mengerti? Generasi yang lebih output oriented, mencari insentif untuk membentuk identitas mereka, dan sedang pusing menempatkan diri di dunia global.
Intinya, menurut saya pribadi, gap generasi itu tak ada. Yang ada adalah gap kerajinan dan intelektualitas. Yang malas belajar pada yang muda dan merasa senior, silahkan menyingkir dan pensiun dini saja.
***
Website ini jalan dengan donasi. Kalau kamu suka yang kamu baca, boleh traktir yang nulis kopi di link ini:
https://trakteer.id/Eseinosa/tip
Thank you.











